GarudaXpose.com I Lumajang — Gunung Semeru kembali bergolak. Statusnya dinaikkan sampai Level IV (Awas), aktivitas erupsi dan guguran lava masih terjadi, sementara awan panas dan banjir lahar kembali menghantui aliran sungai seperti Besuk Kobokan dan daerah di sekitarnya.
Di hilir, kita melihat berita banjir lahar yang menghantam jembatan, tanggul jebol, warga terisolasi, dan para penambang pasir yang panik menyelamatkan diri ketika aliran lahar tiba-tiba turun dari lereng Semeru.
Setiap kali Semeru erupsi, pertanyaan yang sama berulang di ruang-ruang publik:
apakah ini murni bencana alam, atau “teguran” — bahkan “hukuman” — atas ulah manusia yang mengeruk kekayaan Semeru secara sistematis, terstruktur, dan masif?
ADVERTISEMENT
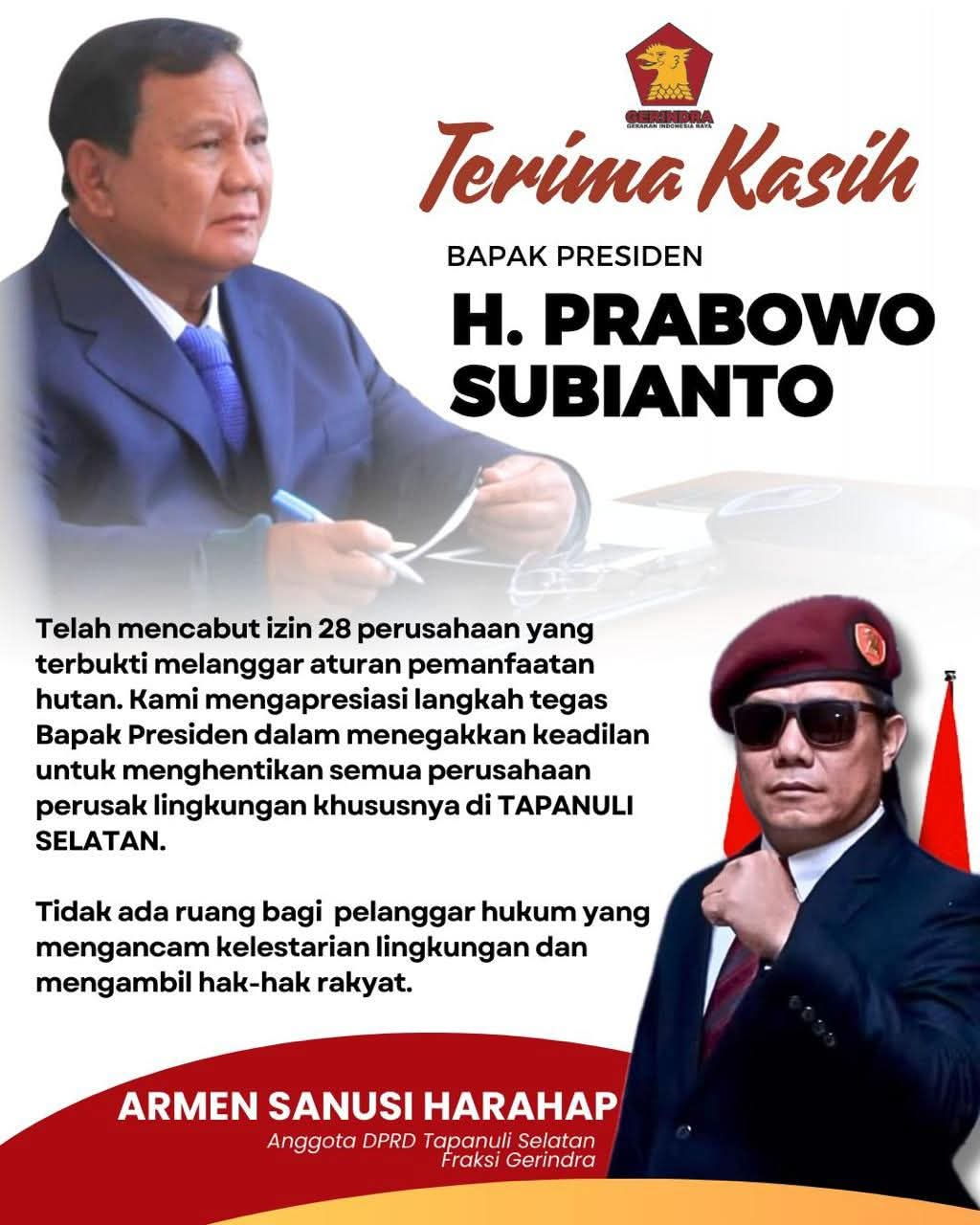
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di telinga banyak orang Indonesia, terutama yang tumbuh besar di era 80–90-an, letusan Semeru dan berita korban sering terasa seperti visualisasi lirik-lirik Ebiet G. Ade, terutama lagu “Untuk Kita Renungkan”. Lagu itu membentang suasana alam yang “mengamuk”, manusia yang terperangah, lalu ajakan untuk bercermin, membersihkan diri, dan bertanya: sejauh apa kita telah berbuat terhadap alam dan sesama?
Editorial ini tidak hendak memonopoli tafsir: apakah erupsi adalah “bencana murni” atau “hukuman ilahi” adalah wilayah keyakinan pribadi yang tidak boleh dipaksa. Tapi kita bisa mengurai tiga lapis refleksi:
1. Lapis ilmiah – Semeru sebagai gunung api aktif dengan siklus geologisnya sendiri.
2. Lapis sosial-ekologis – bagaimana ulah manusia memperparah dampak bencana.
3. Lapis moral-spiritual – sebagaimana disuarakan dalam lagu “Untuk Kita Renungkan”, bahwa bencana seharusnya menjadi cermin, bukan sekadar tontonan.
1. Semeru sebagai Gunung Api Aktif: Bencana Alam yang “Normal”
Secara ilmiah, Semeru adalah gunung api strato yang sangat aktif. Catatan PVMBG dan berbagai media menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir saja terjadi rentetan erupsi disertai awan panas, dengan luncuran hingga belasan kilometer dan kolom abu beberapa ribu meter. Awal tahun 2025, Semeru bahkan tercatat erupsi berulang belasan kali hanya dalam hitungan hari.
Kenaikan status dari Waspada ke Siaga, lalu ke Awas, bukan karena “tiba-tiba Semeru marah”, tetapi karena indikator ilmiah: peningkatan gempa vulkanik, deformasi tubuh gunung, dan aktivitas magma yang naik ke permukaan.
Dari sudut pandang ilmu kebencanaan:
• Erupsi adalah konsekuensi alamiah dari posisi Indonesia di cincin api (ring of fire).
• Semeru, seperti Merapi atau Sinabung, memang “dirancang” secara geologis untuk sesekali meletus.
• Bencana terjadi ketika aktivitas alam bertemu kerentanan manusia: pemukiman di zona bahaya, aktivitas ekonomi di bantaran sungai yang jadi jalur lahar, dan minimnya disiplin terhadap rekomendasi zona aman.
Dalam kerangka ini, erupsi Semeru adalah bencana alam murni: bagian dari dinamika bumi yang sudah berlangsung jauh sebelum manusia datang. Tapi cerita tidak berhenti di situ.
2. Ulah Manusia: Dari “Kekayaan Semeru” ke Kerentanan yang Diciptakan
Pertanyaan yang lebih tajam adalah: mengapa setiap erupsi terasa kian mematikan?
Kita menyaksikan bagaimana penambangan pasir di aliran sungai yang berhulu di Semeru menjadi pemandangan sehari-hari. Truk-truk hilir mudik, ekskavator mengeruk dasar sungai. Dalam sejumlah peristiwa banjir lahar, truk-truk penambang sampai terjebak, penambang dan warga panik menyelamatkan diri.
Ada beberapa masalah struktural yang sering muncul:
1. Eksploitasi Berlebihan dan Tata Kelola Lemah
• Penambangan pasir yang intensif mengubah morfologi sungai, menghancurkan bantaran, dan merusak vegetasi penopang.
• Ketika banjir lahar datang, alur sungai yang sudah “dikeruk” cenderung kehilangan kapasitas alami menahan atau mengarahkan material.
• Jika pengawasan perizinan lemah, tambang-tambang “liar” tumbuh bak jamur, diduga melibatkan jaringan kepentingan yang sistematis, terstruktur, dan masif.
2. Pemukiman dan Infrastruktur di Zona Rawan
• Jembatan, pemukiman, fasilitas umum sering dibangun dekat jalur aliran lahar karena dorongan kebutuhan ekonomi dan akses.
• Setiap letusan besar, berita yang muncul selalu sama: jembatan putus, tanggul jebol, warga terisolasi.
3. Normalisasi Risiko
• Bagi sebagian warga dan penambang, ancaman Semeru adalah “biasa”, hidup berdampingan dengan bahaya sudah menjadi sehari-hari.
• Fenomena ini sangat mirip dengan apa yang dicatat media: penambang tetap bekerja di tengah ancaman lahar dingin, karena tekanan ekonomi dan ketiadaan alternatif penghidupan.
Di titik ini, kita melihat lapisan “bukan lagi murni alam”:
Bukan Semeru yang tiba-tiba kejam, tetapi kebijakan, pengawasan, dan keserakahan manusia yang menjadikan setiap letusan sebagai tragedi sosial-ekologis.
3. “Untuk Kita Renungkan”: Dari Romantisme Bencana ke Etika Lingkungan
Lagu “Untuk Kita Renungkan” sering dikutip setiap kali bencana alam besar terjadi di Indonesia. Liriknya menggambarkan alam yang mengamuk, anak-anak menjerit, lahar dan badai menyapu bersih. Lagu ini menyatukan tiga pesan: refleksi diri, kritik sosial, dan ajakan spiritual.
Beberapa garis besar makna lagu yang relevan dengan situasi Semeru:
1. Bencana sebagai Cermin, Bukan Sekadar “Kutukan”
Lagu ini mengajak kita untuk menengok ke dalam sebelum bicara — melakukan introspeksi, bukan hanya menyalahkan “takdir”. Bagi situasi Semeru, ini bisa dibaca sebagai ajakan untuk jujur:
• Sudahkah tata ruang kita taat pada peta zona bahaya?
• Sudahkah penegakan hukum lingkungan berjalan tegas, bukan tebang pilih?
• Sudahkah keuntungan dari kekayaan pasir Semeru benar-benar kembali pada masyarakat sekitar, atau justru menetes ke segelintir kantong?
2. Kritik terhadap Keserakahan dan Kelalaian
Analisis-analisis tentang lagu ini menyebut adanya kritik halus terhadap manusia yang “bangga dengan dosa-dosa”, terlena dalam kenyamanan, dan mengabaikan nilai keadilan.
Dalam konteks Semeru, “dosa” itu bisa dibaca sebagai:
• Menutup mata terhadap tambang yang merusak.
• Menganggap remeh rekomendasi ilmiah PVMBG demi kelancaran bisnis jangka pendek.
• Memakai jargon pembangunan, tetapi membiarkan warga miskin menjadi tameng risiko bencana.
3. Dimensi Spiritual: “Cambuk Kecil” agar Sadar
Lagu ini menggambarkan bencana sebagai semacam “cambuk kecil” agar manusia kembali sadar pada keterbatasan dan pada Tuhan.
Tanpa harus memutuskan apakah erupsi Semeru adalah hukuman atau bukan, kita bisa menarik pelajaran:
• Bencana mengingatkan bahwa alam bukan objek yang boleh diperah tanpa batas.
• Ada tatanan moral yang menuntut keadilan lintas generasi: anak cucu pun berhak atas Semeru yang tetap kokoh, bukan tinggal cerita dan debu.
4. Erupsi: Bencana Murni, Hukuman, atau Buah Kebijakan?
Daripada bertengkar soal istilah “hukuman” atau “bencana murni”, mungkin pertanyaan yang lebih produktif adalah:
1. Apakah kita siap mengakui kontribusi kesalahan manusia dalam memperparah dampak erupsi?
• Jika kita terus membiarkan penambangan yang merusak, pemukiman di zona merah, dan tata ruang yang mengabaikan peta rawan bencana, maka setiap letusan akan berulang sebagai bencana buatan manusia (human-induced disaster).
2. Apakah negara hadir bukan hanya saat bantuan logistik dibagikan, tetapi sejak jauh hari dalam bentuk regulasi tegas dan pengawasan sungguh-sungguh?
• Penegakan aturan pertambangan, pajak galian C, hingga penertiban tambang dan portal liar bukan sekadar isu administratif, tapi bagian dari ikhtiar mencegah korban.
3. Apakah masyarakat mau terlibat sebagai pengawas moral?
• Warga, akademisi, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil perlu bersuara ketika ada indikasi perampokan kekayaan Semeru yang sistematis, terstruktur, dan masif.
• Sunyi di ruang publik sering kali memelihara kejahatan struktural.
Dalam bahasa Ebiet, mungkin kita bisa membacanya sebagai ajakan: “kita mesti berjuang memerangi diri” — memerangi keserakahan, kemalasan intelektual, dan rasa puas dengan jawaban sederhana bahwa “ini sudah takdir”.
Penutup: Dari Ratap Menjadi Sikap
Erupsi Semeru hari ini seharusnya tidak lagi kita sambut hanya dengan ratap, siaran langsung dramatis, dan unggahan media sosial. Ia harus menjadi momen sikap.
1. Sikap Ilmiah:
Mengakui bahwa Semeru adalah gunung api aktif; patuh pada rekomendasi PVMBG, menjauh dari zona bahaya, dan memprioritaskan keselamatan jiwa di atas kepentingan ekonomi sesaat.
2. Sikap Sosial-Politik:
Menuntut transparansi dan penegakan hukum atas pengelolaan tambang, pajak galian, dan praktik-praktik yang diduga merampok kekayaan Semeru.
Jika benar ada jaringan kepentingan yang mengambil keuntungan dari pasir Semeru tanpa peduli keselamatan rakyat, maka itu bukan sekadar soal pelanggaran administrasi — itu pengkhianatan terhadap masa depan Lumajang dan sekitarnya.
3. Sikap Moral-Spiritual:
Sejalan dengan pesan “Untuk Kita Renungkan”, bencana adalah ajakan untuk membersihkan hati dan nurani:
• Mengembalikan alam sebagai amanah, bukan komoditas semata.
• Menghadirkan empati nyata kepada para korban, bukan sekadar belas kasihan musiman.
• Mengubah gaya hidup dan pola kebijakan agar lebih selaras dengan keberlanjutan.
Pada akhirnya, mungkin kita tidak pernah akan sepakat apakah erupsi Semeru ini adalah “bencana murni” atau “hukuman”. Tetapi jika setiap letusan melahirkan perubahan nyata dalam cara kita mengelola alam, menata kebijakan, dan memperlakukan sesama, maka derita yang terjadi tidak menjadi sia-sia.
- Di titik itulah, Semeru bukan lagi sekadar gunung yang mengerikan, melainkan cermin raksasa yang memaksa kita, sebagaimana judul lagu itu, untuk sungguh-sungguh “meresapi dan merenungkan” siapa sebenarnya yang selama ini bertindak seperti perampok atas kekayaan Semeru: alam, atau justru kita sendiri.( Narasumber : Basuki Rakhmad ( Oki) Advokad, Konsultan Hukum dan Auditor Hukum)





















